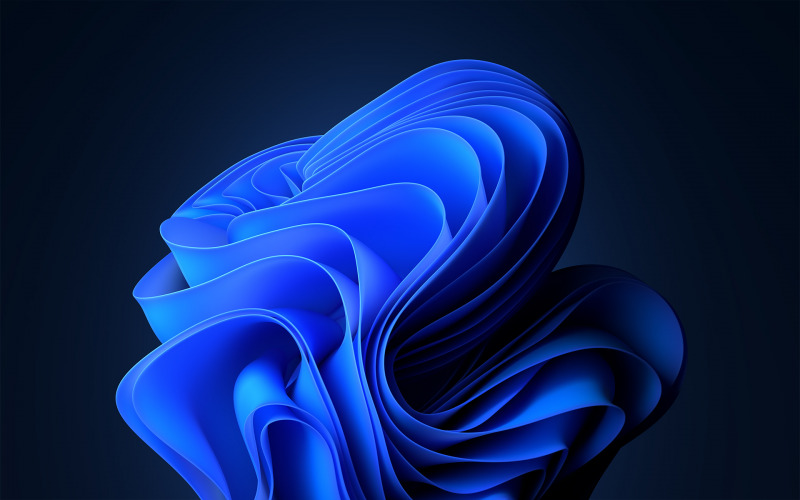Telset.id – Pernahkah Anda merasa terjebak dalam lingkaran lagu nan sama di Spotify? Rekomendasi algoritma nan semestinya membuka bumi musik baru justru menyajikan daftar putar nan monoton dan aman. Inilah realita pahit nan dihadapi jutaan pendengar musik digital hari ini.
Terrence O’Brien, penyunting akhir pekan The Verge dengan pengalaman 18 tahun di industri teknologi, mengungkapkan gimana algoritma rekomendasi musik nan awalnya dijanjikan sebagai solusi justru berubah menjadi masalah. Dalam kajian mendalamnya, O’Brien menelusuri perjalanan dari era penemuan musik manual menuju kekuasaan algoritma nan mengubah lanskap musik modern.
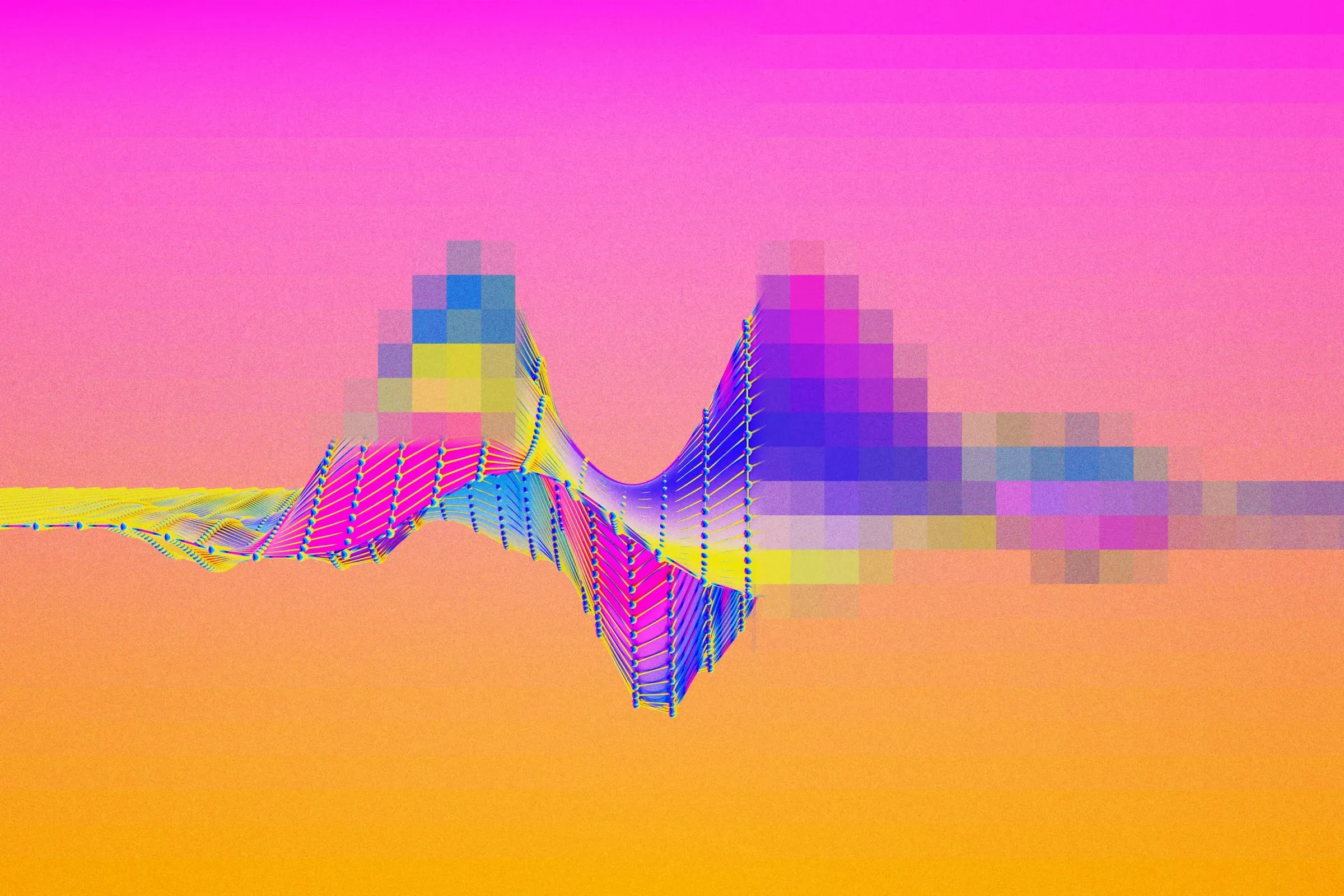
Bayangkan tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Setiap Selasa, O’Brien mempunyai ritual khusus: turun dari kereta di 8th Street, mampir ke toko musik Other Music, membeli CD baru, dan mendengarkannya sembari melangkah menuju Staten Island Ferry. “Bahkan jika tidak ada album baru nan saya tunggu minggu itu, saya bakal membeli sesuatu,” kenangnya. Tempat unik di toko itu menampilkan rekomendasi staf nan ditulis tangan di kartu indeks – sistem kurasi manusia murni nan justru efektif menemukan musik berkualitas.
Era itu berhujung dengan datangnya revolusi digital. Pandora mempelopori algoritma rekomendasi musik dengan Proyek Music Genome nan menganalisis lagu berasas karakter terukur seperti “jenis kelamin vokalis utama, tingkat distorsi gitar listrik, jenis vokal latar.” Sistem ini memang novel pada masanya, tetapi sudah menunjukkan masalah fundamental: kecenderungan memutar 10 lagu nan sama berulang-ulang.
Ketika Spotify mendarat di AS tahun 2011 dengan katalog 15 juta lagu, segalanya berubah. Perusahaan ini dari awal mengangkat pendekatan algoritmik sepenuhnya. Puncaknya adalah peluncuran Discover Weekly tahun 2015 – playlist 30 lagu nan diperbarui setiap minggu menggunakan teknologi canggih dari The Echo Nest nan dibeli Spotify tahun 2014.
Strategi Spotify: Bukan Musik, Tapi Pengisi Waktu
Di kembali antarmuka nan user-friendly, Spotify mempunyai agenda tersembunyi. Menurut mantan tenaga kerja nan dikutip wartawan Liz Pelly dalam bukunya “Mood Machine,” CEO Daniel Ek pernah mengatakan, “satu-satunya pesaing kami adalah keheningan.” Pernyataan ini mengungkap filosofi inti Spotify: mereka bukan perusahaan musik, melainkan pengisi waktu.
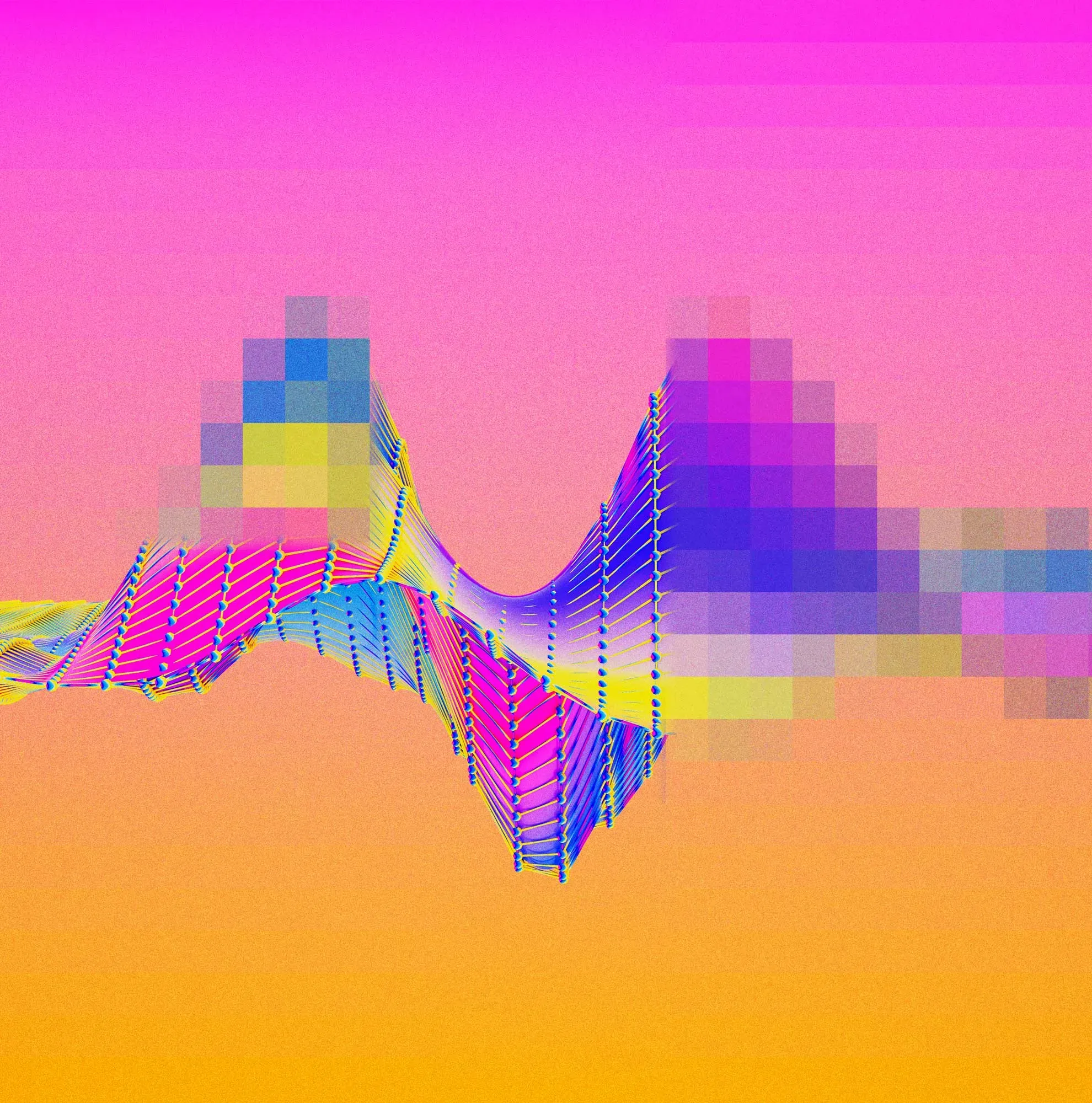
“Sebagian besar pendengar musik sebenarnya tidak tertarik mendengarkan musik itu sendiri. Mereka hanya memerlukan soundtrack untuk momen dalam hari mereka,” jelas mantan tenaga kerja tersebut. Pendekatan ini memengaruhi langkah kerja algoritma Spotify. Tujuannya bukan membantu Anda menemukan musik baru, melainkan membikin Anda terus mendengarkan selama mungkin dengan menyajikan lagu-lagu paling kondusif nan tidak membikin Anda menekan tombol berhenti.
Lebih mengkhawatirkan lagi, Spotify apalagi berkolaborasi dengan jasa perpustakaan musik dan perusahaan produksi melalui program berjulukan Perfect Fit Content (PFC). Program ini menciptakan artis “hantu” alias tiruan nan membanjiri Spotify dengan lagu-lagu nan secara unik dirancang untuk terdengar menyenangkan dan bisa diabaikan. Inilah musik sebagai konten, bukan seni.
Efek Domino nan Merusak Industri Musik
Dampak algoritma tidak berakhir di pengalaman pendengar. Layanan streaming memberikan info luar biasa banyak kepada label rekaman tentang apa nan didengarkan orang. Dalam lingkaran umpan kembali nan berbahaya, label mulai memprioritaskan artis nan terdengar seperti apa nan sudah didengarkan orang. Dan apa nan didengarkan orang adalah apa nan disarankan algoritma.
Artis, terutama nan baru mencoba menembus industri, betul-betul mengubah langkah mereka berkarya untuk bermain lebih baik di era streaming nan digerakkan algoritma. Lagu menjadi lebih pendek, album lebih panjang, dan intro menghilang. Hook didorong ke depan lagu untuk mencoba menarik perhatian pendengar segera, dan hal-hal seperti solo gitar nyaris menghilang dari musik pop.
Palet bunyi nan diambil artis menjadi lebih kecil, aransemen menjadi lebih disederhanakan, musik pop menjadi rata. Seperti nan diungkapkan kajian teknologi rekomendasi berbasis pencarian, sistem nan semestinya memudahkan justru bisa membatasi eksplorasi.
Studi MIDiA nan diterbitkan September 2025 mengungkap temanan mengejutkan: “semakin berjuntai pengguna pada algoritma, semakin sedikit musik nan mereka dengar.” nan lebih mengejutkan, sementara penemuan musik baru secara tradisional dikaitkan dengan kaum muda, “anak usia 16-24 tahun lebih mini kemungkinannya daripada usia 25-34 tahun untuk menemukan artis nan mereka sukai dalam setahun terakhir.” Gen Z mungkin mendengar lagu nan mereka sukai di TikTok, tetapi mereka jarang menyelidiki lebih jauh untuk mendengarkan lebih banyak musik dari artis tersebut.
Kebangkitan Anti-Algoritma dan Masa Depan Penemuan Musik
Keletihan terhadap algoritma telah menumpuk untuk beberapa waktu. Apple menjadikan kurasi manusia sebagai titik jual utama jasa musiknya, dengan melibatkan nama-nama besar seperti Jimmy Iovine dan Zane Lowe. Namun baru-baru ini, pemberontakan terhadap algoritma mendapatkan momentum.

Bandcamp Daily telah menjadi penopang penemuan musik sejak 2016, dan situs tersebut meluncurkan Bandcamp Clubs tahun 2025. Layanan ini memberikan satu album pilihan manusia setiap bulan, wawancara artis, dan pesta mendengarkan langsung kepada pelanggan. Qobuz memang mempunyai mesin rekomendasi algoritmik, tetapi jauh lebih konsentrasi pada sisi editorialnya di Qobuz Magazine.
Gen Z mungkin lebih mini kemungkinannya menemukan artis baru nan mereka sukai daripada beberapa generasi tua. Tetapi mereka juga memimpin kebangkitan radio kampus. Radio terestrial sekali tampak seperti format nan sekarat, tetapi banyak sekolah sekarang melaporkan mereka tidak mempunyai cukup slot waktu untuk menampung semua calon DJ.
Bahkan iPod menikmati kebangkitan kembali. iPod klasik dijual ratusan dolar di eBay, dan seluruh subkultur, meskipun kecil, muncul di sekitar memodifikasinya untuk memperpanjang masa pakai baterai, meningkatkan penyimpanan, dan menambahkan kenyamanan modern seperti Bluetooth dan USB-C. Seperti nan ditunjukkan dalam rekomendasi TWS Oppo terbaik, teknologi audio individual terus berkembang di luar ekosistem streaming utama.
Pada tahap ini, anti-algoritma sendiri telah menjadi seluruh aliran konten. Terutama di YouTube, di mana pembuat membikin video tentang meninggalkan streaming, menghentikan doomscrolling, dan gimana algoritma telah meratakan budaya.
Tentu saja, begitu sesuatu menjadi tren, hanya masalah waktu sebelum perusahaan mulai mencoba mencari langkah untuk menguangkannya. Spotify telah memperkenalkan fitur untuk mencoba mengatasi keluhan tentang algoritmanya, termasuk keahlian untuk mengecualikan lagu dari profil selera Anda. Tetapi perusahaan juga memperkenalkan fitur kurasi manusia baru seperti nan terlihat dalam playlist “Teman Perjalananmu”.
Lebih banyak perusahaan mungkin bakal mulai menawarkan jalan keluar lantaran kelelahan algoritma tumbuh. Namun, pada akhirnya, perusahaan bakal mencari langkah untuk menciptakan ilusi penemuan nan kebetulan. Mereka bakal menyajikan rekomendasi algoritmik, tetapi mengemasnya dengan langkah nan terasa lebih alami.
Tidak susah membayangkan masa depan di mana playlist nan secara lahiriah dikurasi manusia secara algoritmik disesuaikan untuk mengecualikan lagu nan tidak persis cocok dengan riwayat mendengarkan Anda. Atau satu di mana rekomendasi algoritmik ditempatkan secara lembut di tempat nan mudah ditemukan, membikin Anda merasa seperti tanpa sengaja menemukan rekaman baru sendiri. Anda tetap bakal dimanipulasi oleh algoritma; hanya bakal lebih susah untuk dikenali.
Kebangkitan vinyl adalah bagian dari sentimen anti-algoritma. Mungkin dimulai sekitar tahun 2007, tetapi memuncak pada 2020-an. Pendengar mulai merangkul kembali media bentuk dan format album. Awalnya, didorong oleh artis independen dan toko musik kecil, tetapi akhirnya apalagi artis seperti Taylor Swift ikut serta, menjual lebih dari 1,3 juta kopi The Life of a Showgirl di vinyl pada minggu pertamanya.
Last.FM adalah sistem rekomendasi musik awal lainnya nan mengandalkan analitik data. Sistem ini melacak apa nan Anda dengarkan dan menyarankan band berasas apa nan disukai pengguna lain dengan selera serupa. Meskipun tetap ada, rekomendasi algoritmik original di Spotify dan sejenisnya membuatnya menjadi usang. Meskipun menemukan kehidupan kedua di Discord, rupanya.
Pertanyaannya sekarang: apakah kita bisa menemukan keseimbangan antara efisiensi algoritma dan keautentikan kurasi manusia? Atau apakah kita bakal selamanya terjebak dalam lingkaran rekomendasi nan semakin menyempit? Jawabannya mungkin terletak pada kesadaran kita sebagai pendengar untuk aktif mencari di luar apa nan disajikan algoritma kepada kita.